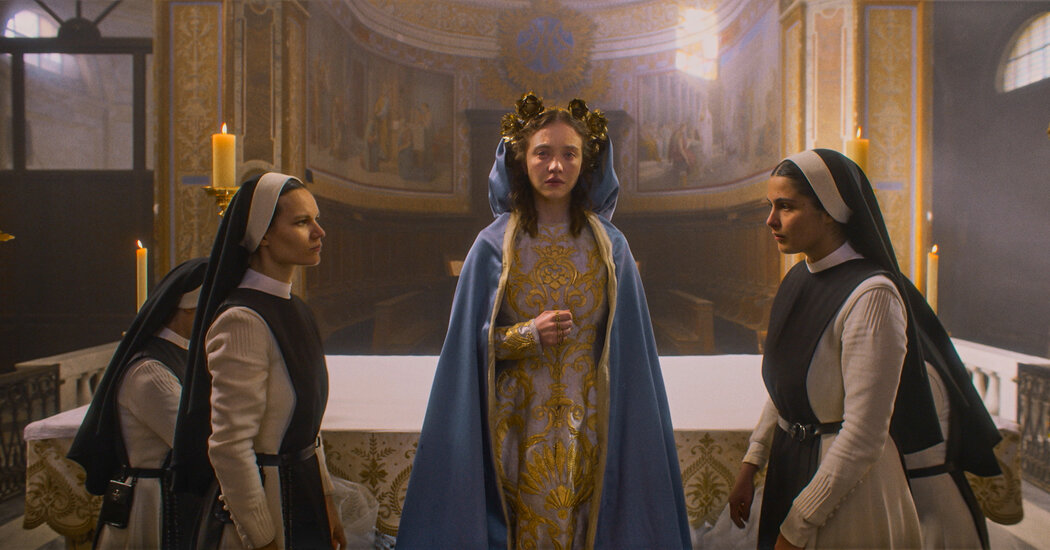Dari Madame Eglantine yang sangat sombong oleh Chaucer dalam “The Canterbury Tales,” dengan anjing peliharaannya yang dimanja dan sikap Prancis sekuler, hingga Sister Jude yang kejam oleh Ryan Murphy di “American Horror Story: Asylum” tahun 2012, seorang wanita yang mengenakan gaun tidur merah di bawah jubahnya dan tidak segan untuk minum anggur komuni, penggambaran fiksi tentang biarawati selalu berhasil menarik dan membingungkan imajinasi. Bagaimana mungkin tidak? Sumpah kesucian dan kemiskinan para suster serta aura kerahasiaan yang menyelimuti kehidupan mereka di biara sangat bertentangan dengan nilai-nilai Barat modern tentang seks, uang, dan ketenaran. Banyak dari kita juga pernah bertemu dengan biarawati dalam kehidupan nyata kita—saya menghabiskan sebagian besar kelas empat menghadap sudut ruangan atas perintah tegas Sister Rosalia—dan dibiarkan dengan apa yang saya sebut sebagai kefascinan naluriah. Tetapi jika minat estetika terhadap biarawati adalah hal yang abadi, juga benar bahwa setiap beberapa tahun sekali, seperti tren mode atau wabah virus, biarawati mengalami momen budaya yang sangat terkonsentrasi. Momen tersebut kita alami sekarang.
Mungkin yang paling tajam, paling rumit dari gambaran biarawati kontemporer adalah “Doubt: A Parable” karya dramawan John Patrick Shanley. Pertama kali dipentaskan di Broadway pada tahun 2005, baru-baru ini selesai penampilannya di sana, disutradarai oleh Scott Ellis. (Tiga anggota pemeran telah dinominasikan untuk Penghargaan Tony.) Drama ini menceritakan kisah Sister Aloysius yang tegas (Amy Ryan dalam pertunjukan Ellis), kepala sekolah Katolik di Bronx tahun 1964, yang, berdasarkan firasat seorang novis polos, Sister James (Zoe Kazan), menuduh Pastor Flynn, imam paroki (Liev Schreiber), berbuat tidak senonoh terhadap satu-satunya siswa kulit hitam di sekolah (ibu siswa tersebut diperankan oleh Quincy Tyler Bernstine). Ini adalah drama detektif tanpa penyelesaian, kisah moral dengan ambiguitas tak terpecahkan di jantungnya. Ellis mengatakan dia tertarik untuk menggelar drama tersebut karena emosi judulnya terasa lebih penting dari sebelumnya di dunia yang semakin polarisasi. “Dengan segala hal yang ada dalam masyarakat saat ini, hitam dan putih dari semuanya, merah dan biru,” katanya, “keraguan merupakan tempat yang paling penting untuk ditinggali.”
Rebecca Sullivan, penulis buku tahun 2005 “Visual Habits: Nuns, Feminism and American Postwar Popular Culture,” mengatakan bahwa “di saat-saat keraguan yang dalam,” kita cenderung melihat representasi budaya tentang biarawati muncul. Dia mencatat bahwa banjir film nunsploitation pada tahun 1960-an dan ’70-an—subgenre sinematik yang kampiun, provokatif, sebagian besar dari Eropa di mana biarawati diseksualisasi, disiksa, atau dihuni—terjadi pada masa pergolakan sosial yang besar. Feminisme gelombang kedua sedang berkembang, sekularisme semakin meningkat, dan Konsili Vatikan Kedua, yang berlangsung antara 1962 dan ’65, telah membawa masuk berbagai reformasi gereja: Misalnya, biarawati didorong untuk keluar dari biara dan melayani komunitas serta tidak lagi diwajibkan mengenakan jubah. Status ambang dari para suster—mereka merupakan wanita mandiri yang juga menunjukkan “ketundukan subversif,” seperti yang disebutkan Sullivan, terhadap institusi patriarki—membuat mereka menjadi simbol-simbol yang kaya dan kompleks, sandi untuk mengeksplorasi perasaan zaman tersebut tentang wanita secara umum.